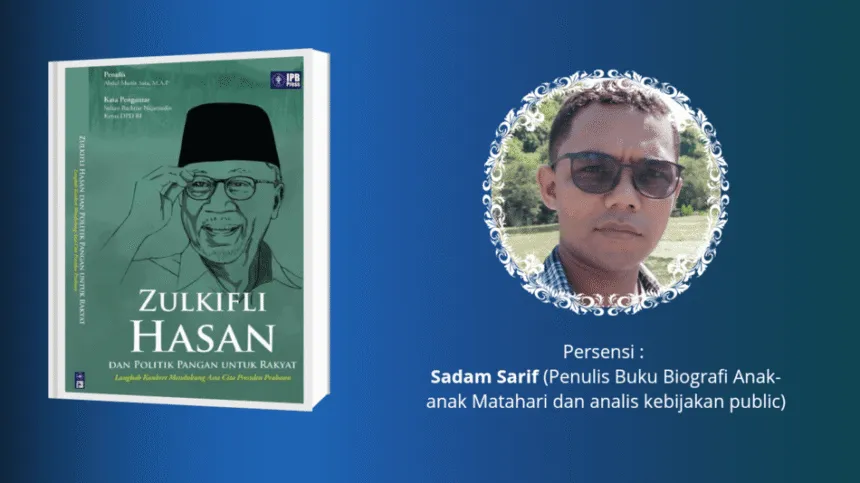Persensi : Sadam Sarif (Penulis Buku Biografi Anak-anak Matahari dan analis kebijakan public)
Karya : Abdul Munir Sara
Penerbit : IPB Press, 2025, 212 halaman
RESENSI, suararakyat.id – Buku ini adalah potret lengkap tentang bagaimana politik pangan dijalankan bukan sekadar sebagai kebijakan teknis, tetapi sebagai komitmen moral. Abdul Munir Sara merangkai narasi biografis dan analisis kebijakan publik untuk menggambarkan Zulkifli Hasan—yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan—sebagai figur yang menggabungkan pengalaman hidup seorang anak petani dengan tanggung jawab strategis di panggung nasional.
Sejak halaman awal, pembaca disuguhi pengantar Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang menekankan perbedaan fundamental Zulkifli Hasan dibanding pejabat pada umumnya: ia memandang pangan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar komoditas ekonomi. Dari konsep justice as fairness John Rawls hingga pandangan Michael Sandel tentang moral publik, buku ini menempatkan Zulkifli sebagai pemimpin yang memadukan teori keadilan dengan kerja teknokratik—mulai dari reformasi kewajiban pasokan dalam negeri (DMO), penetapan harga pembelian pemerintah (DPO), stabilisasi harga, operasi pasar murah, hingga membangun sistem logistik pangan desa berbasis koperasi.
Narasi penulis mengalir dari latar biografis yang sarat detail. Zulkifli Hasan lahir di Pekon Pisang, Lampung, dari keluarga petani sederhana. Ia tumbuh dalam dunia di mana harga gabah menentukan suasana rumah, dan pupuk yang terlambat datang berarti kegelisahan bagi kepala keluarga. Pengalaman itu membentuk sikapnya terhadap politik: bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi seni mempertahankan kehidupan bersama. Politik baginya adalah keberpihakan yang terukur, berpijak pada realitas rakyat kecil.
Buku ini memaparkan dengan rinci perjalanan Zulkifli Hasan dari aktivis Muhammadiyah, pengusaha telur, legislator, Menteri Kehutanan, hingga Menteri Perdagangan yang kemudian dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Pangan. Setiap fase kariernya dibingkai dengan peristiwa-peristiwa konkret—misalnya, bagaimana ia menangani lonjakan harga minyak goreng dengan mengatur ulang DMO dan DPO secara disiplin, sehingga harga kembali ke HET dalam waktu dua bulan. Di sini, penulis mengaitkan langkah Zulhas dengan tesis Joseph Stiglitz tentang perlunya intervensi negara untuk mengoreksi kegagalan pasar.
Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya menautkan narasi lapangan dengan teori kebijakan publik. Abdul Munir Sara meminjam kerangka Multiple Streams Framework John Kingdon untuk menjelaskan mengapa kepemimpinan Zulkifli efektif: ia mampu menangkap momentum pertemuan antara masalah (krisis pangan), solusi (digitalisasi dan koperasi desa), dan dukungan politik (mandat presiden). Pendekatan incremental ala Charles Lindblom juga terlihat dalam cara ia membangun reformasi pangan secara bertahap, berbasis bukti, dan melibatkan banyak aktor—dari Bulog hingga BUMDes.
Tema swasembada pangan dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo menjadi salah satu pilar buku ini. Penulis menunjukkan bahwa bagi Zulkifli Hasan, swasembada bukanlah kebijakan proteksionis sempit, tetapi strategi geostrategis: memastikan ketersediaan pangan sebagai syarat kedaulatan nasional. Ia mendorong decentralized food resilience—lumbung pangan desa yang dikelola koperasi, diperkuat digitalisasi, dan didukung pembiayaan dari LPDB atau skema blended finance. Di sini, pembaca menemukan pandangan etis bahwa tanah tetap milik petani, hasil panen dikelola bersama, dan negara hadir sebagai fasilitator, bukan pengambil alih.
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) menjadi simbol strategi Zulkifli Hasan. Ia memotong rantai tengkulak, memodernisasi manajemen koperasi, dan menghubungkannya dengan pasar lewat teknologi digital. Abdul Munir Sara menggambarkan ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan upaya membangun kontrak sosial baru: swasta menjadi mitra, bukan penguasa; negara menjadi penjaga keadilan distribusi, bukan penonton.
Kisah intervensi harga pangan menjelang Ramadhan 2025 menjadi bab yang hidup. Data BPS menunjukkan deflasi umum, tetapi inflasi kelompok makanan tetap positif. Zulkifli membaca ini sebagai tanda daya beli masih bertahan dan menggunakannya untuk menjustifikasi operasi pasar murah. Stok beras, gula, dan minyak dijamin cukup, distribusi dipercepat, spekulan ditindak. Harga dijaga bukan sekadar demi stabilitas ekonomi, tetapi untuk menghindari keresahan sosial. Di sini, penulis menempatkan Zulhas dalam tradisi pemikiran Karl Polanyi—bahwa pasar harus dijinakkan demi keberlangsungan hidup bersama.
Penulis juga menyoroti pendekatan teknokratik Zulkifli dalam mengelola rantai pasok pangan. Dashboard pangan digital yang menghubungkan data panen, harga, dan stok dari desa hingga pusat menjadi instrumen kontrol yang membalik struktur kekuasaan pangan: dari elit ke rakyat. Ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen bahwa kelaparan terjadi bukan karena kurangnya pangan, tetapi karena akses yang terputus.
Menariknya, buku ini tidak menghindar dari dimensi politik praktis. Sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan harus menyeimbangkan agenda partai dengan tanggung jawab kementerian. Namun, Abdul Munir Sara menggambarkannya sebagai “operator lapangan” yang memilih fokus pada kerja teknis ketimbang pencitraan. Survei yang menempatkannya sebagai Menko berkinerja terbaik tidak ia jadikan bahan kampanye pribadi, melainkan momentum untuk memperkuat sistem pangan nasional.
Gaya penulisan buku ini menggabungkan narasi jurnalisme sastra dengan kutipan teoritis yang padat. Referensi akademis dari Elinor Ostrom, Dani Rodrik, hingga M. Dawam Rahardjo memperkuat argumen bahwa kebijakan pangan memerlukan keseimbangan antara sains, etika, dan partisipasi masyarakat. Namun, kekayaan teori ini tidak membuatnya kering, karena penulis selalu mengaitkannya dengan adegan konkret: pertemuan Zulhas dengan petani, inspeksi gudang Bulog, atau diskusi di pasar tradisional.
Secara substansi, buku ini memiliki dua kontribusi utama. Pertama, ia mendokumentasikan transformasi kebijakan pangan di era Prabowo melalui lensa seorang pelaksana lapangan. Kedua, ia menyuguhkan model kepemimpinan yang memadukan akar sosial, keberanian politik, dan kecermatan teknis. Bagi pembaca yang tertarik pada kebijakan publik, buku ini menjadi studi kasus tentang bagaimana visi presiden dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang menyentuh level desa.
Meski demikian, pembaca kritis mungkin akan merasa buku ini cenderung simpatik terhadap tokoh yang diangkat. Kritik terhadap potensi hambatan atau kegagalan program—misalnya risiko digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur desa, atau tantangan koperasi menghadapi persaingan pasar modern—tidak dibahas mendalam. Namun, dalam kerangka buku biografis-politis, pilihan ini bisa dimaklumi. Fokusnya adalah membangun narasi keberpihakan, bukan audit kebijakan.
Akhirnya, Zulkifli Hasan dan Politik Pangan untuk Rakyat menawarkan lebih dari sekadar kisah seorang menteri. Ia adalah refleksi tentang politik sebagai ruang pengabdian, tentang bagaimana kerja teknokratik bisa berpihak, dan tentang keyakinan bahwa kedaulatan bangsa bermula dari sawah, lumbung, dan pasar yang dikelola dengan adil. Dengan bahasa yang memadukan data, teori, dan cerita hidup, Abdul Munir Sara berhasil menyampaikan bahwa di balik angka produksi dan stok beras, ada wajah-wajah rakyat yang menjadi alasan utama politik pangan harus terus diperjuangkan.
Buku ini layak dibaca oleh pembuat kebijakan, aktivis koperasi, akademisi, dan siapa pun yang percaya bahwa keadilan sosial tidak mungkin tercapai tanpa keadilan pangan. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah arus globalisasi dan dominasi pasar, negara tetap punya peran esensial: memastikan setiap piring di meja rakyat terisi—bukan karena belas kasihan, tetapi karena sistem yang adil dan berpihak.
Mengenal Sosok Pahlawan Pangan, Resensi Buku ‘Politik Pangan sebagai Jalan Pengabdian Zulkifli Hasan’